 Novel The Da Vinci Code (TDVC) yang laris manis itu, meskipun menimbulkan protes keras umat Kristiani, tampaknya adalah blessing in disguise. Kajian terhadap keyakinan dan praktik Kristiani (atau yang disebut Kristologi) pun semakin marak. Di Indonesia, sejak diterjemahkan dan diterbitkannya TDVC, belasan judul, entah itu yang mengulas ataupun yang membantahnya, terbit dan tidak sedikit yang menjadi best seller.
Novel The Da Vinci Code (TDVC) yang laris manis itu, meskipun menimbulkan protes keras umat Kristiani, tampaknya adalah blessing in disguise. Kajian terhadap keyakinan dan praktik Kristiani (atau yang disebut Kristologi) pun semakin marak. Di Indonesia, sejak diterjemahkan dan diterbitkannya TDVC, belasan judul, entah itu yang mengulas ataupun yang membantahnya, terbit dan tidak sedikit yang menjadi best seller.Bukan semata umat Kristiani yang konon, seperti terjadi di Eropa, kembali rajin mengunjungi gereja dan membaca buku-buku keagamaan tetapi umat non-Kristiani pun perlahan mulai tertarik mempelajari atau, paling tidak, sekedar ingin mengetahui keyakinan ini.
Buku Bacalah Bibel: Merajut Benang Merah Tiga Iman karya Dr. Thomas McElwain, ini tampaknya juga ditempatkan penerbitnya, Penerbit Citra, untuk ikut meramaikan fenomena di atas.
Namun, patut digarisbawahi, berbeda dengan para pendahulunya—seperti sebut saja TDVC (dan karya-karya yang mengomentarinya) dan Holy Blood Holy Grail—yang mendasarkan isinya atas analisis kontroversial simbol-simbol dan asumsi-asumsi arkeologis yang secara faktual masih diragukan, Bacalah Bibel menyajikan suatu kajian yang artikulatif terhadap Alkitab melalui pendekatan analisis teks. Dalam konteks ini, buku ini lebih pantas dihadirkan di atas meja bedah ilmiah yang objektif daripada, tentu saja, TDVC yang fiktif itu.
Selain itu, karya McElwain, yang edisi Inggrisnya berjudul Islam in the Bible, ini berbeda dengan analisis-analisis terhadap Alkitab yang pernah ada, paling tidak, dengan mempertimbangkan dua hal sebagai berikut.
Pertama, McElwain tidak semata-mata melakukan analisis teks melalui penekanan pada kesepadanan konseptual (conceptual equivalent), seperti yang telah banyak dilakukan, tetapi lebih pada kesepadanan linguistik (linguistic equivalent), sesuatu yang menurutnya lebih objektif meskipun terkesan rigid (hal. 23). Meskipun demikian, ia tidak lantas mengabaikan kesepadanan konseptual karena kesepadanan linguistik cenderung melewatkan beberapa hal yang mungkin relevan. Kenyataan tersebut menjadikan buku ini unik karena, bagaimanapun, pendekatan linguistik terhadap Alkitab mensyaratkan sang peneliti memiliki kemampuan dalam banyak bahasa, khususnya Ibrani dan Yunani kuno—dan untungnya McElwain adalah salah seorang kampiun dalam bidang ini.
Kedua, McElwain berangkat dari asumsi bahwa adalah suatu keniscayaan jika terdapat keselarasan di antara keyakinan dan praktik Yudaisme-Kristiani yang terdapat dalam Alkitab (bukan yang kini dipraktikkan) dengan keyakinan dan praktik Islam karena ketiganya adalah berasal dari Sumber yang sama dan dijaga oleh manusia-manusia suci dalam mata rantai genealogis yang sama pula. Hal ini kontras dengan, misalnya Ahmad Deedat, seorang kristolog Muslim, yang sejak awal berasumsi bahwa Alkitab telah terdistorsi. Asumsi McElwain pun sama sekali bertolak belakang dengan apologi-apologi Josh McDowell yang semata berangkat dari doktrin-doktrin Kristen (baca Gereja).
Inilah keunikan posisi McElwain. Melalui buku ini, ia mengkritik dua kutub diametral sekaligus: asumsi Deedat yang terlalu simplistik terhadap Alkitab dan asumsi McDowell yang bias doktrin teologis. Uniknya pula, dua kutub yang dikritiknya itu, Deedat dan McDowell, pernah terlibat dalam sebuah debat.
Tak heran, melalui dua keunikan tersebut, Bacalah Bibel menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang akan mengejutkan banyak pembaca dari latar belakang agama apa pun. Mengejutkan karena McElwain mampu, tidak hanya membantah argumen kedua kutub diametral di atas, melakukan rekonsiliasi terhadap banyak hal yang sejak lama dipandang sebagai konflik antar-kitab suci.
Persoalan ketuhanan Yesus, misalnya, didekati McElwain dengan membedah persoalan penerjemahan terkait karakter tiap-tiap bahasa biblikal plus beberapa detail kasus linguistik.
Kata kyrious (dalam Alkitab berbahasa Yunani) atau lord (dalam KJV) yang kerap mendahului kata Yesus — yang diterjemahkan Tuhan dalam Alkitab LAI (terjemahan versi Lembaga Alkitab Indonesia)—seringkali secara tidak hati-hati dijadikan dasar bagi doktrin ketuhanan Yesus. Walaupun kata tersebut, pada beberapa bagian Alkitab, digunakan bagi Tuhan, penggunaannya tidaklah terbatas pada makna tersebut. Dalam kasus Yesus, adalah lebih bijaksana—dengan mempertimbangkan karakter-karakter yang logis bagi Tuhan—untuk menggunakan kata tersebut dengan makna ‘tuan’ seperti layaknya panggilan kehormatan bagi manusia. Bagi McElwain, kasus polisemi pada kata tersebut menandakan bahwa Alkitab tidak pernah benar-benar mengafirmasi ketuhanan Yesus (hal. 90).
Demikian pula, ungkapan Bapa untuk Tuhan dan Anak Tuhan bagi Kristus—sering dijadikan dalil bagi klaim-klaim Trinitarian—seperti yang dilakukan McDowell—ataupun tuduhan-tuduhan kepalsuan Alkitab—yang dilancarkan kristolog Muslim, seperti Deedat. Dengan menggunakan pendekatan diakronik, McElwain menunjukkan bahwa bahasa-bahasa semitik (khususnya Ibrani yang biblikal) jarang menggunakan kedua ungkapan di atas dengan makna harfiahnya, yakni keturunan biologis. Lebih daripada itu, ia pun menyatakan bahwa tak seorang pun penganut Kristiani yang meyakini bahwa kedua ungkapan itu bermakna hubungan biologis. Toh, kalaupun ada, hal itu karena sebagian besar bahasa modern yang digunakan untuk menerjemahkan Alkitab—berbeda dengan bahasa-bahasa asalnya—tampaknya tidak memiliki alternatif makna selain makna harfiahnya yang biologis itu (hal. 73).
Kemudian, melalui pendekatan interteks terhadap teks-teks suci Kristiani, McElwain sampai pada kesimpulan bahwa ungkapan Bapa digunakan Alkitab untuk merepresentasikan lima makna:
[1] ayah menurut makna harfiah biologis;
[2] leluhur;
[3] pencipta atau prototipe;
[4] seseorang yang memberikan nasehat atau informasi; dan
[5] seseorang yang harus dipatuhi secara mutlak (hal. 74-75).
Sekali lagi, dengan mempertimbangkan sifat-sifat niscaya ketuhanan plus karakter-karakter hubungan Yesus dengan Sang Bapa, maka, menurutnya, definisi terakhirlah yang paling sesuai dalam hubungannya dengan Tuhan.
Mengenai Anak Tuhan, lagi-lagi McElwain—seraya memerinci bagian-bagian Alkitab yang menggunakan ungkapan tersebut dalam makna metaforisnya—mengungkapkan bahwa ternyata: [1] ungkapan Anak Tuhan di dalam Alkitab tidak semata ditujukan pada Yesus, seperti pada Ayub 1:6 dan Kejadian 6:2; [2] Yesus sendiri, ketika menjawab tuduhan para rabbi, menolak pemaknaan Anak Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri dalam Yohanes 10:34-36. Menurut Kristus, dalam rangkaian ayat itu, apa yang dimaksud Anak Tuhan adalah ‘yang disucikan Tuhan’ dan ‘yang diutus-Nya ke dalam dunia’. (hal. 94-95).
Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh McElwain di atas secara implisit mengimplikasikan bahwa:
[1] serangan al-Quran terhadap Trinitas dan penuhanan Yesus sama sekali tidaklah ditujukan pada Alkitab tetapi pada interpretasi-interpretasi yang meragukan terhadap Alkitab, dan praktik-praktik keyakinan yang berkembang jauh setelah masa penulisan Alkitab. Dengan ini, pandangan bahwa telah terjadi konflik antar-kitab suci tidaklah dapat dibenarkan;
[2] adanya perbedaan karakter kenabian di antara tiga nabi Abrahamik (Musa, Yesus, dan Muhammad). Musa lebih bernuansa eksoterik sementara Yesus esoterik, dan Muhammad adalah sintesis dari dua pendahulunya itu. Karakter esoterik Yesus tampak pada ajaran-ajarannya yang lebih menekankan aspek moral ketimbang hukum dan pada sabda-sabdanya yang bernuansa gnostik. Inilah tampaknya yang, bagi McElwain, menyebabkan umat Kristiani seringkali salah memahami sabda-sabdanya, apalagi ditambah dengan tidak dicantumkannya bahasa asal dalam Alkitab terjemahan.
Memang persoalan-persoalan teologis nyaris menghabiskan sepertiga halaman buku ini. Namun selain itu, yang, menurut penulis resensi ini, paling menarik adalah analisis McElwain terhadap riwayat genealogis para patriarki yang demikian detail disebutkan dalam Alkitab serta interpretasinya terhadap frase eets hakhayyim (Ibrani), the tree of life (Inggris), dan pohon kehidupan (Indonesia) yang dalam Alkitab disebutkan pertama kali pada Kejadian 2:9.
Melalui analisis historis genealogis para patriarki dalam Alkitab, McElwain mendapati bahwa akan selalu ada manusia-manusia yang dipilih Tuhan untuk membimbing umat manusia pada setiap zamannya. Manusia-manusia ini tidak selalu hadir di tengah masyarakat manusia dalam formalitas kenabian. Namun yang pasti, mereka merepresentasikan otoritas Tuhan dalam memberikan penilaian segera (on spot evaluation) atas hukum mengenai problem-problem partikular dan temporal di tengah masyarakat dan pada zaman mereka masing-masing. Dengan kehadiran mereka, umat manusia akan terhindar dari formalisme dan relativisme hukum. Di sini, pandangan McElwain selaras dengan asumsi-asumsi gnostik, di antaranya yang diungkapkan sufi besar Islam, Ibn Arabi, bahwa selama masih ada, maka dunia ini tidak akan pernah vakum dari kehadiran seorang manusia sempurna (the perfect man).
Ketika menginterpretasi frase eets hakhayyim (pohon kehidupan), McElwain menggunakan sejenis hermeneutika kuno yang pernah diterapkan pada Taurat dan kemudian diadaptasi sebuah aliran sufi Persia, Hurufiyyah, menjadi metodologi Hurufi. Huruf-huruf dalam frase tersebut secara kabalistik dipisahkan menjadi ‘ayin, tsade, he, khet, yod, dan mem. Semuanya berjumlah tujuh: salah satu angka istimewa dalam tradisi-tradisi agama Abrahamik. ‘Ayin adalah huruf awal bagi nama Ali, tsade bagi nama Shadiq, he bagi nama Hasan, khet bagi nama Husain, dan mem bagi nama Muhammad dan Musa. Sisanya, yod, merupakan huruf awal bagi nama Tuhan dalam bahasa Ibrani (YHWH). Tidak diragukan lagi, McElwain tengah memecahkan kode-kode biblikal yang mendukung klaim dua belas imam Muslim Syi’ah. Meskipun terdapat dua belas imam, hanya terdapat enam, yang tiga di antaranya digunakan bagi lebih daripada satu imam (hal. 129).
Namun, bagi McElwain, eets hakhayyim tampaknya hanyalah sebuah awal. Dalam buku ini, ia menunjukkan bahwa bilangan dua belas—selain tujuh—menjadi begitu sentral dalam keseluruhan Alkitab. Raja-raja, hakim-hakim, nabi-nabi kecil, dan bahkan murid-murid Kristus pun semuanya seolah dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan jumlah dua belas.
Demikianlah, dalam banyak problem lainnya yang dipandang sebagi konflik antar-kitab suci—seperti persoalan Ishak ataukah Ismail yang hendak dikorbankan; pengorbanan Yesus di tiang salib; pernikahan; dan kesucian—studi McElwain dalam buku ini tidak hanya menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang khas bagi para pembacanya tetapi juga patut diacungi jempol dalam kaitan dengan konsistensinya pada prinsip studi biblikal yang dianutnya: tidak ada distorsi dalam Alkitab dan Alkitab sebagai teks suci tiga agama Abrahamik.
Prinsip ini penting—selain karena berbeda dengan yang sudah-sudah— untuk memulai sebuah dialog yang lebih objektif, jujur, dan tulus menuju kesepahaman antara Yudaisme, Kristen, dan Islam, dalam bingkai satu kitab, Alkitab, yang hingga batas-batas tertentu diakui otoritasnya oleh mayoritas penganut tiga agama tersebut. (Irman Abdurrahman/icc-jakarta.com)
Satu Kitab, Tiga Agama
Judul Buku : Bacalah Bibel: Merajut Benang Merah Tiga Iman
Penulis : Thomas McElwain
Penerjemah : Muhammad Musaddiq
Penerbit : Citra
Cetakan : I, Juni 2006
Halaman : vi + 333 halaman








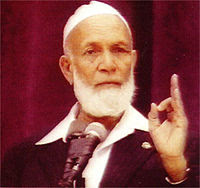
No comments:
Post a Comment